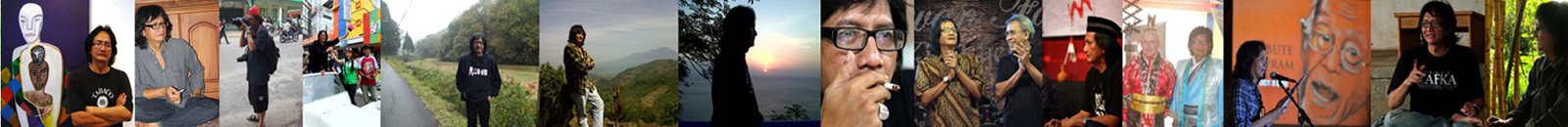MENDADAK SUNDA
Acep Zamzam Noor
Acep Zamzam Noor
KETIKA mendengar ada belasan orang Sunda menjadi calon menteri dalam kabinet 2009-2014 mendatang saya merasa senang, lebih senangnya lagi karena tiga dari belasan orang itu berasal dari Tasikmalaya, daerah asal saya. Kesenangan saya terus bertambah karena di antara calon menteri asal Tasikmalaya akhir-akhir ini fotonya sering muncul di koran dengan memakai baju kampret dan ikat kepala barangbang semplak, yang konon merupakan pakaian khas Sunda. Saya bukan hanya senang namun juga bersyukur karena ide pencalonan ini telah memberi efek positif terhadap budaya Sunda, paling tidak dalam hal pakaian. Kenapa? Karena sebelumnya saya sering melihat foto calon menteri tersebut dalam pakaian khas Timur Tengah, terutama kalau sedang mengikuti acara istighosah.
Saya baru tahu belakangan kalau belasan orang Sunda yang dicalonkan menjadi menteri tersebut merupakan hasil survey yang telah dilakukan oleh sebuah tim independen. Tim tersebut menuntut jatah 20 persen kursi menteri untuk orang Sunda kepada presiden terpilih. Entah apa alasannya dengan angka 20 persen tersebut, apakah karena penduduk tatar Sunda jumlahnya banyak, apakah karena kwalitas orang Sunda unggul dibanding suku lain, atau karena secara geografis bertetangga dengan Jakarta. Belasan orang yang diusulkan menjadi menteri, kebanyakan dari kalangan birokrasi seperti gubernur, walikota, bupati serta akademisi, menurut tim independen merupakan representasi dari masyarakat dan budaya Sunda. Dengan kata lain, mereka sangat pantas sebagai wakil masyarakat dan budaya Sunda untuk menduduki jabatan tinggi itu.
Permintaan jatah menteri yang selama ini tidak pernah dilakukan orang Sunda mana pun tentu saja menuai pro dan kontra. Bagi para calon menteri beserta tim suksesnya sudah pasti akan pro alias setuju, namun di pihak lain tak sedikit masyarakat yang justru mempertanyakannya. Usep Romli HM menganggap permintaan jatah menteri tersebut sebagai sikap nyarayuda alias meminta-minta kekuasaan yang tidak selayaknya dilakukan mengingat urusan menteri adalah hak prerogatif presiden. Dhipa Galuh Purba melihatnya sebagai “jeruk makan jeruk” karena salah seorang calon menteri yang terjaring justru ketua tim surveynya sendiri. Hawe Setiawan membandingkan kasus ini dengan orang-orang miskin yang mengantri pembagian dana BLT. Sementara di koran-koran lokal banyak surat pembaca yang mempertanyakan soal metode survey serta kapasitas sebagian calon. ”Jangan-jangan malah bikin malu orang Sunda,” kata salah satu surat pembaca.
Meskipun saya merasa sependapat dengan rekan-rekan di atas, namun rasa senang terhadap mereka yang sudah dicalonkan menjadi menteri tidak menguap begitu saja. Saya tetap berharap bahwa survey ini akan ada hikmahnya di kemudian hari. Bagi mereka yang sudah memakai baju kampret dan ikat kepala barangbang semplak teruslah memakainya, terlepas apakah nanti terpilih atau tidak. Dengan terbiasa memakai pakaian khas Sunda mudah-mudahan akan berlanjut dengan meningkatkan apresiasi terhadap budaya Sunda. Paling tidak bisa dimulai dengan meluangkan waktu untuk menghadiri acara-acara kesenian Sunda, membaca karya-karya sastra Sunda, memelihara tradisi-tradisi Sunda, dan lebih mantap lagi jika diikuti dengan menggali kearifan-kearifan Sunda. Itulah hikmah yang saya maksud.
Seandainya upaya peningkatan apresiasi tidak dilakukan, maka kedudukan budaya Sunda tak ada bedanya dengan agama yang selama ini hanya dijadikan “dagangan” politik. Bukankah para politisi bisa mendadak menjadi apa saja ketika ada kepentingan di belakangnya? Bisa mendadak berpakaian putih-putih ala Pangeran Diponegoro, bisa berkostum hitam-hitam ala pendekar silat Cimande, bahkan kalau perlu tidak berpakaian sama sekali. Tergantung ke mana angin politik sedang berhembus.
Sebagai penutup tulisan ini, perkenankan saya mengutip sebuah cerita dari khazanah sastra lisan Sunda:
Alkisah, Si Kabayan mempunyai tetangga yang akan mengawinkan anaknya dengan menggelar pesta besar-besaran. Semua penduduk di kampung itu diundangnya, kecuali Si Kabayan. Karena merasa keberadaannya tidak dianggap sama sekali, Si Kabayan pun mencari akal bagaimana caranya agar tetap bisa ikut pesta seperti yang lain. Maka pada saat pesta sedang berlangsung, Si Kabayan tiba-tiba bertelanjang bulat di antara para tamu undangan, lalu ngadepaan lincar (menjengkal papan penjepit bilik) sambil menari-nari. Tentu saja ulah Si Kabayan ini menarik perhatian orang sehingga tuan rumah terpaksa turun tangan. ”Kabayan, kenapa kamu telanjang begitu kayak anak kecil?” hardik tuan rumah. ”Biarin kayak anak kecil juga, toh kalau saya dianggap dewasa pasti akan diundang seperti yang lain,” jawab Si Kabayan.
Cerita di atas bagi saya sangat dalam maknanya. Di kalangan masyarakat Sunda sikap nyarayuda, mengemis, meminta-minta atau apapun namanya, apalagi dengan cara menentukan target (seperti minta jatah menteri 20 persen) merupakan perbuatan kurang terpuji, yang dalam cerita di atas dengan sangat tepat disimbolkan sebagai perbuatan yang tak ada bedanya dengan memperlihatkan aurat sendiri. Si Kabayan nekad memperlihatkan auratnya hanya karena ingin menarik perhatian orang. Hanya karena ingin diundang ke pesta perkawinan.
(2009)